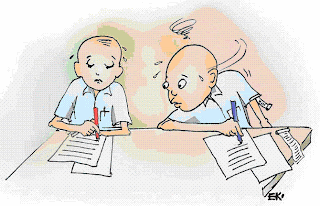Oleh : Muhammad Khambali
Alangkah
malangnya penghuni bumi saat ini, ia hidup di zaman yang aneh. Mungkin juga
konyol. Tak tau kenapa tiba-tiba ada yang hilang---mungkin lupa---entah kenapa.
Padahal ‘sesuatu yang hilang’ itu merupakan hal esensi, sebuah eksistensi kita
sebagai makhuk bumi yang berakal budi. Taukah, sesuatu yang hilang itu bernama
‘nilai’, entah itu nilai budaya, etik, moral, juga agama. Celakalah kita.
Sebab,
nilai setidaknya memberi
kita sebuah keniscayaan. Menunjukkan kita akan garis-garis imajiner yang
membekali kita dalam laku juga pijakan berfikir. Konon, akibat ‘sesuatu yang
hilang’ itu, kini manusia memandang hidup ini sebagai sesuatu yang absurd,
tanpa batasan-batasan yang jelas. Bingung menentukan mana yang benar dan
mana yang salah, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Lalu tumbuhlah
partikularisme, egoisme, juga sinisme. Pada akhirnya, entitas akan altruisme
pun perlahan memudar. Mungkin juga hilang.
Tak
sebatas itu, kemudian muncul anomali nilai yang mengagas sebuah semantika baru
dalam ranah pendidikan. “Nilai” baru itu tereduksi dalam ruang sempit yang kita
kenal sebagai nilai ulangan, nilai UTS, nilai UAS, nilai Raport, atau nilai
ijazah. Ia telah menjadi Neo-keniscayaan
yang mengukuhkan diri sebagai batu pijakan tunggal dalam dunia pendidikan kita.
Maka, lahirlah kolonialisme, serta Komunalisme pecinta ‘nilai’.
Permasalahan
lalu muncul, ketika nilai dijadikan sebagai Absolute
value untuk mengukur
keberhasilan teatrikal ruang kelas, maka terbentuklah pemikiran kerdil yang
mencari jalan pintas. Muaranya adalah drama Ujian Nasional, siswa moncontek
saat ulangan, makelar soal, jual-beli Ijazah, dan entah apa lagi. Weber dengan
muram menyebut ini sebagai ”nalar instrumental”, bagian dari modernitas yang
akhirnya akan membawa manusia ke dalam ”kerangkeng besi”.
Selanjutnya
pertanyaan terbesar---barangkali sebuah kebodohan---adalah siapa yang patut
dipersalah? Lantas apakah ini sebagai bentuk kompromi dari ‘sesuatu yang
hilang’ itu. Entahlah. Tapi mungkin ini sebabnya, dalam buku Arete, Sokrates
pernah berkata; bila ada orang jahat, kejahatanya tidak pernah bersifat
sengaja, sebab kejahatan itu muncul dari ketidaktahuan atau ignorance.
Manusia
tidak pernah menginginkan kejahatan karena kejahatan akan memberikan keburukan
kepadanya. Apa yang disebut jahat, seringkali dilakukan orang justru karena ia
menganggap hal tersebut sabagai baik. Hal ini menjadi sebuah realitas ketika
seorang guru menyuruh muridnya yang dianggap pintar agar “membantu”
teman-temannya yang “bodoh” ketika ujian. Karena guru tersebut “tahu” itu
merupakan hal yang baik.
Lalu
ini diperjelas oleh muridnya, Plato. ia mengutarakan dua alasan. Pertama, yang
namanya kejahatan dan kekeliruan itu tidak bisa dipisahkan. Orang jahat
biasanya adalah orang yang keliru, itu sebabnya kebaikan selalu dekat dengan
kebenaran. Seorang murid atau mahasiswa yang mencontek ketika ulangan
dikarenakan kekeliruan ia dalam menafsirkan sekolah atau kuliah. Ia sekolah
untuk mengejar nilai atau IP, bukan untuk mengali ilmu sebanyak-banyaknya.
Yang
kedua, bahwa bila hasrat manusia sudah terdidik dengan baik, maka otomatis ia
akan cenderung mengikuti pemikiran (pengetahuan akan kebaikan). Baik Sokrates
maupun Plato yakin bahwa Right
action follows inevitably from right knowledge.
Artinya, bila orang mengetahui benar-benar apa yang baik, maka
tindakannya akan mengikuti hal-hal tersebut, mengingat semua orang selalu
menginginkan apa yang terbaik baginya.
Disinilah
pendidikan menjadi titik permasalahan dari proses pemberian “pengetahuan”.
Pengetahuan yang dimaksud bukanlah teori-teori abstrak objektif, akan tetapi ia
adalah entitas sebuah kebijaksanaan (wisdom). Pendidikan kita saat ini
hanya sekedar pengajaran. Memberi ilmu, tak mendewasakan. Melahirkan homo
sapiens, bukan homo significan dan homo luden. ia tak mampu menjernihkan, akan
mana yang keliru dan tidak keliru, tetapi justru membuatnya keruh, sehingga
muncul ignorance.
Radhar
Panca Dahana dalam esai sarjana
lahir dari sebuah mumi mengungkapkannya
dengan sangat apik. Konon, Pendidikan telah membungkus kenyataan lewat selimut
kata-kata dan retorika saintik. Dan manusia tak lagi mengenali daun dari
kelembutan bulunya, atau embun yang membasahi permukaannya. Daun telah
mengalami metamorfosa, secara semantik maupun gramatik, kita sudah tak lagi
memiliki daun, sebagaimana kita sudah tak lagi memiliki dunia ini.
Pendidikan
justru membuat kita merasa kian bodoh. Tak memberi kita “pengetahuan”.
Pendidikan telah dikhianati oleh misi awalnya sendiri. Sebab pendidikan saat
ini bukan lagi dipergunakan untuk membuat manusia mengenal dirinya sendiri dan
lingkungannya. Namun, ia telah menjadi ruang untuk pencarian
kemenangan-kemenangan akan nilai atau philonikon, juga
untuk mengejar nama besar dan rasa hormat akan gelar atau Philotimon.
Dan akhirnya pendidikan melahirkan mumi yang gerak hidupnya terpusat untuk
menimbun uang dan harta benda atau philokhrematon.
Seharusnya
pendidikan layaknya tarian Syiwa-Nataraja bagi Sanusi Pane dalam Caping-nya Goenawan
Mohamad. Ia adalah ‘jalan ringkas mencapai kemerdekaan’. Jiwa akan merdeka jika
kita membiarkan diri menari dan ‘membakar segala ikatan buta’ yang kita buat,
jika dalam gerak itu, sang penari tak dijajah oleh hasil, oleh ‘tujuan’. Jika
kita sekolah atau kuliah tak sekedar hal konyol untuk mengejar nilai, gelar,
atau harta, maka pendidikkan akan kembali hakikatnya sebagai ruang untuk
memanusiakan-manusia. Lebih dari itu, pendidikan akan menjadikan kita seorang Philomates, cinta
akan belajar.
***